Perdebatan soal pemulangan 689 WNI eks ISIS yang tersebar di Syuriah dan Turki, yang akan dikembalikan ke Indonesia saat ini menjadi salah satu isu nasional yang ramai diperbincangkan.
Isu itu menjadi viral lantaran kepulangan mereka dianggap menjadi salah satu ancaman terhadap stabiltas keamanan negara. Lebih dari itu, ISIS di Indonesia sudah beberapa kali melakukan aksi-aksi teror. Mereka bahkan membentuk jaringan dengan beberapa organisasi-organisasi Islam radikal seperti Jama’ah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Itu sebabnya, bagi pemerintah dan sebagian kalangan, penolakan atas kepulangan eks-kombatan ISIS itu adalah hal yang wajib untuk dilakukan.
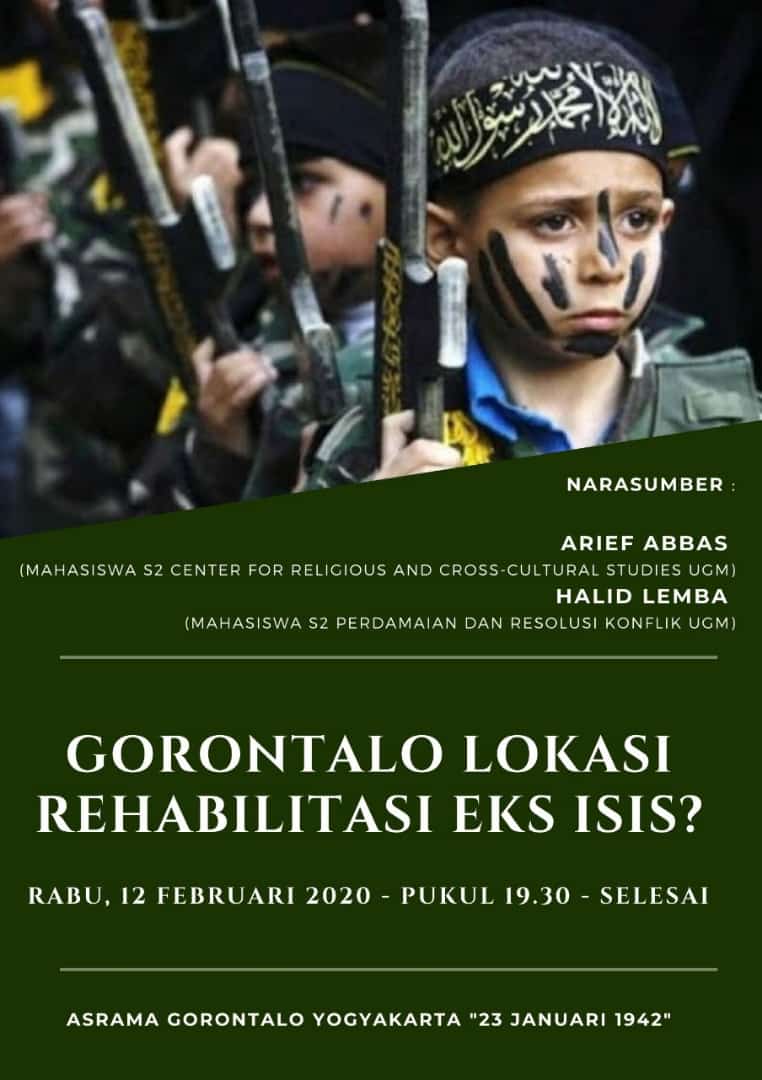
Namun demikian, di antara beberapa pihak yang menolak hal tersebut, saya kira pemulangan eks ISIS ke Indonesia perlu dipertimbangkan lagi dengan beberapa alasan. Sebab, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menyatakan bahwa pemulangan eks ISIS ke Indonesia dapat dilakukan asal dengan komitmen de-radikalisasi, sebagaimana pernah dilakukan mereka pada tahun 2017 silam.
Dengan pertimbangan tersebutlah bagi saya, bagaimana pun juga, para eks ISIS itu adalah warga negara Indonesia. Mereka adalah anak kandung Ibu Pertiwi. Membakar paspor tidak serta-merta menghilangkan identitas mereka sebagai warga negara Indonesia. Sehingga, upaya untuk tidak memulangkan mereka akan dilihat sebagai penelantaran negara terhadap warga negaranya sendiri.
Kedua, keputusan untuk memulangkan eks ISIS ke Indonesia bisa dilihat adalah komitmen pemerintah sekaligus bukti terhadap kemenangan ideologi Pancasila; bahwa, memang benar Pancasila itu dapat diimplementasikan menjadi semacam tools dan instrumen untuk mengembalikan nasionalisme. Selain itu, jika hal ini coba dikaitkan dengan janji untuk memberantas ideologi radikal yang masuk sebagai salah satu janji pemerintah Indonesia, pemulangan eks anggota ISIS hal ini bisa jadi menjadi alasan yang dapat mengukuhkan bahwa Indonesia tercatat memiliki kontribusi untuk memberantas ideologi radikal yang saat ini sedang marak dan menjamur.
Di lain sisi, saya kira, ketakutan pemulangan eks ISIS ke Indonesia ini merupakan bagian dari sesat berpikir (logical fallacy). Sebab, bukannya direhabilitasi, para eks ISIS di mata negara justru menjadi momok yang menakutkan sebelum mereka disentuh. Padahal, seharusnya negara memiliki komitmen untuk menjaga dan mengembalikan kesadaran nasionalisme mereka yang hilang sejak meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan ISIS. Selanjutnya, negara dalam hal ini tidak memiliki perangkat metodologis berbasis kearifan lokal, dan justru menanggapi isu-isu semacam ini dengan cara yang represif dan defensif.
Memang, berdasarkan amanat PP 77/2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Pasal 28 huruf B disebutkan bahwa deradikalisasi dapat dilaksanakan melalui: 1) Pembinaan wawasan kebangsaan; 2) pembinaan wawasan keagamaan; 3) Pembinaan Kewirausahaan. Namun demikian, saya kira cara semacam ini tidak dapat menyelesaikan akar persoalan yang ada. Sebab masalah identitas itu terikat erat dengan ideologi, tempat dan kebudayaan. Sehingga, salah satu cara yang saya kira paling ampuh untuk meruntuhkan ideologi para eks ISIS adalah dengan mengembalikan kesadaran kultural masyarakat yang terpapar ideologi radikal.
Selanjutnya, dalam mengelaborasi instrumen tersebut, pemerintah belum memiliki arena rehabilitasi. Yang dimaksud dengan arena rehabilitasi di sini adalah sebuah lokasi dengan prasyarat sebagai daerah yang memiliki kondisi sosio-historis minim konflik, praktik toleransi yang kuat, kearifan lokal yang terjaga, serta komitmen dan kesetiaan kepada Republik Indonesia yang menyejarah. Di titik inilah sebenarnya instrumen tersebut harus dijalankan secara operasional dan bukan sekadar wacana belaka. Apalagi, selama ini kita tahu bahwa proses rehabilitasi yang dilakukan negara selama ini terjadi secara panoptikon: diberlakukan secara ofensif, satu arah dan kebanyakan terjadi dari penjara ke penjara, kamp-kamp konsentrasi, serta asrama-asrama penampungan.
Melihat berbagai prasyarat di atas, Gorontalo menjadi arena yang siap dalam proses deradikalisasi eks-ISIS karena memiliki basis kearifan dan sistem sosial yang kuat. Hal tersebut terbukti bahwa Gorontalo adalah daerah yang tercatat tidak pernah memiliki sejarah konflik antar etnis maupun agama. Selanjutnya, Gorontalo juga memiliki ragam kearifan lokal yang menjadi atmosfir positif dalam proyek deradikalisasi. Sebagai contoh misalnya, ada kebudayaan lokal yang bernama Tolopani, yakni sebuah prinsip untuk menghargai sesama manusia, apa pun identitas, jenis kelamin, warna kulit, perbedaan agama, dan latar etnis mereka; dan Tayade, sebuah prinsip untuk berbagi kepada sesama. Kedua model sistem sosial yang menyejarah ini bahkan jauh lebih tua ratusan tahun sebelum Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948 dicetuskan.
Lebih dari itu, dalam hal komitmen dan kesetiaan kepada Republik Indonesia, Gorontalo tidak perlu diragukan lagi. Sebab dalam sejarah, Gorontalo tercatat merupakan satu-satunya daerah yang pertama kali memerdekakan diri sekaligus mengukuhkan nasionalisme terhadap Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka (1942). Selain itu, ketika berbagai daerah di Sulawesi mendukung pemberontakan terhadap pemerintah pusat lewat gerakan PERMESTA pada tahun 1957, Gorontalo adalah satu-satunya daerah yang menunjukkan kesetiannya terhadap republik ini dengan tidak ikut terlibat dalam gerakan tersebut. Sehingga, bisa dipastikan dalam proses penanganan dan rehabilitasi eks ISIS ini, Gorontalo bakal menjadi tempat yang paling cocok untuk dijadikan sebagai arena rehabilitasi eks ISIS.
Tetapi kemudian, hal ini tidak bisa terlaksana tanpa komunikasi antar stakeholder dan para pemangku kebijakan setempat. Sehingga, untuk melaksankannya, dibutuhkan keberanian dan kerja-kerja kolektif serta terukur untuk melaksanakannya. Sebab polemik pemulangan eks ISIS ke Indonesia terang diketahui adalah hal yang kompleks dan tidak mudah untuk diselesaikan.[]
Pokok Pikiran Ini merupakan Catatan Funco Tanipu (Dosen Sosiolog UNG, sementara melakukan study Doktoral UGM)



